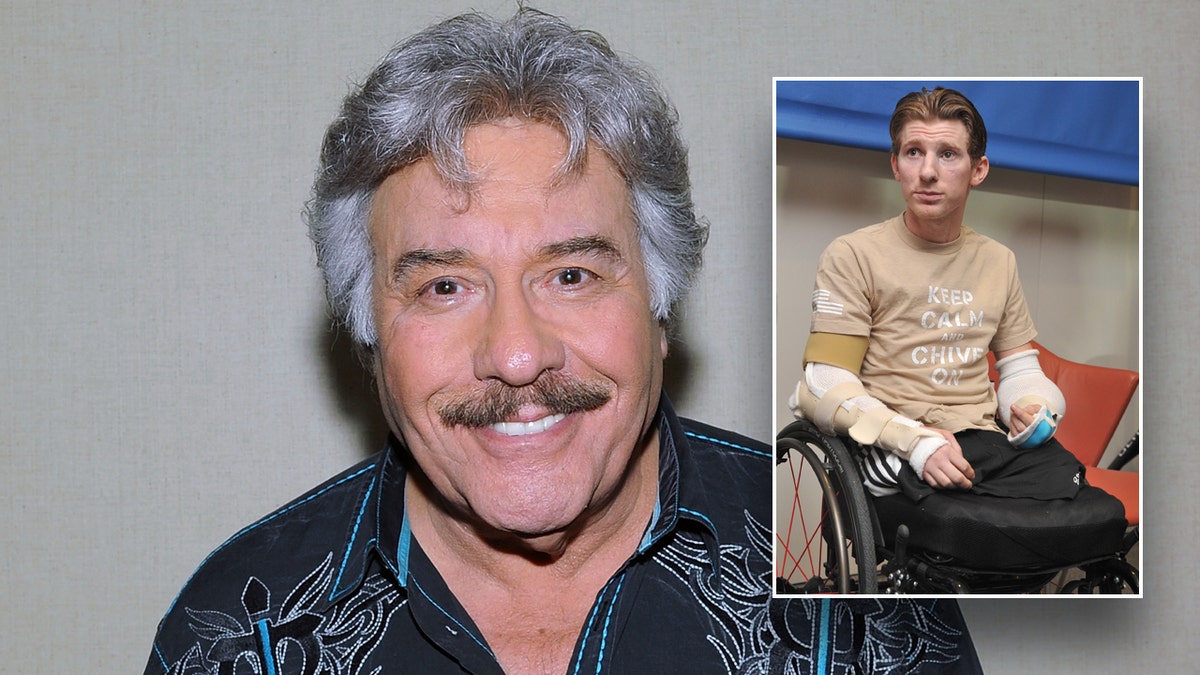Pencari suaka asal Pakistan semakin banyak yang tinggal di Bangkok, sehingga menambah jumlah pengungsi perkotaan di dunia

BANGKOK – Mereka adalah keluarga kelas menengah di Pakistan, tinggal di apartemen tiga kamar tidur yang nyaman dengan dapur modern dan PlayStation untuk ketiga anaknya. Sang ayah fasih berbahasa Inggris dan menjalankan perusahaan pindahannya sendiri sementara sang ibu belajar seni.
Ancaman pembunuhan yang ditandatangani oleh kelompok ekstremis Muslim – dengan tiga peluru terpasang – memaksa keluarga Kristen untuk meninggalkan semuanya 18 bulan lalu. Sekarang mereka tinggal di sebuah kamar kosong di Bangkok, di mana anak-anak berbagi tempat tidur ganda dan orang tuanya tidur di lantai. Mereka memasak di atas kompor propana di balkon kecil. Sebuah gambar Yesus – sumber kenyamanan dan masalah mereka – tergantung di bagian dalam pintu.
Hal ini semakin menjadi kehidupan para pencari suaka dan pengungsi. Lebih dari separuh dari 14 juta pengungsi dan pencari suaka yang berada di bawah mandat badan pengungsi PBB tidak tinggal di kamp-kamp yang sering berhubungan dengan mereka. Jumlahnya semakin banyak yang tinggal di kota besar dan kecil di seluruh dunia. Di seluruh Asia, dari India hingga Kepulauan Pasifik, terdapat sekitar setengah juta “pengungsi perkotaan”, menurut badan tersebut.
Keluarga Pakistan tidak lagi mengkhawatirkan nyawa mereka, namun mereka menghadapi ketakutan lain – penangkapan, kelaparan, dan kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah bisa hidup bebas.
Karena tidak dapat bekerja secara legal dan tanpa status hukum di Thailand, mereka dan orang-orang seperti mereka harus tetap bersembunyi, mencari pekerjaan serabutan dan sumbangan dari gereja, kelompok bantuan dan individu. Anak-anak mereka, yang semuanya berusia sekolah dasar, tidak bersekolah dan menghabiskan sepanjang hari di dalam rumah.
“Kami hanya ingin menyelamatkan hidup kami,” kata sang ayah, yang masa berlaku visanya melebihi batas dan, seperti lusinan pencari suaka lainnya yang diwawancarai untuk cerita ini, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut ditangkap. “Kami tidak tahu apa-apa ketika kami tiba. Sekarang kami hanya berusaha bertahan hidup.”
Banyak pencari suaka menaruh harapan mereka pada hadiah yang sulit didapat: pemukiman kembali di negara ketiga seperti AS atau Kanada melalui proses yang diawasi oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Hal ini dapat memakan waktu lima tahun atau lebih, dan seringkali tidak terjadi sama sekali.
Lonjakan pengungsi perkotaan menantang negara-negara yang enggan menampung pengungsi seperti Thailand, yang pada masa lalu mengizinkan pengungsi dari negara-negara sekitarnya masuk ke kamp-kamp perbatasan namun tidak secara hukum mengakui pencari suaka atau pengungsi.
Relatif mudahnya mendapatkan visa turis Thailand, salah satu alasan mengapa jumlah pencari suaka di Bangkok meningkat beberapa kali lipat dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih dari 8.000, menurut angka dari UNHCR. Kontingen terbesar dan paling cepat berkembang di sini berasal dari Pakistan, kata para ahli, sementara kelompok besar lainnya berasal dari Sri Lanka, Vietnam, Somalia dan Suriah.
Ketika mereka mendarat, banyak yang terkejut saat mengetahui bahwa mereka ditangkap segera setelah visa mereka habis. Mereka berharap UNHCR akan melindungi mereka, namun aktivis pengungsi mengatakan polisi Thailand umumnya mengabaikan surat-surat PBB yang menyatakan mereka sebagai “orang-orang yang menjadi perhatian”. Thailand tidak pernah menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 yang melindungi hak-hak pengungsi; begitu pula negara tetangga Malaysia dan Indonesia, tempat ribuan pencari suaka masih tinggal.
Oleh karena itu, para pengungsi perkotaan ini hidup dalam ketidakpastian, lebih bebas dibandingkan mereka yang berada di lingkungan kamp, namun dalam beberapa hal lebih rentan.
“Ini adalah masa depan,” kata Mireille Girard, perwakilan Thailand untuk UNHCR. “Kita benar-benar perlu beradaptasi untuk memberikan bantuan di wilayah perkotaan.”
Meski mengalami kesulitan, banyak yang mengatakan mereka tidak akan pernah kembali ke rumah. Mereka terlalu takut.
“Kami hanya akan menghadapi ancaman yang sama lagi,” kata ibu asal Pakistan tersebut. “Saya tidak siap mengorbankan anak-anak saya untuk itu.”
___
Di Pakistan, pasangan tersebut dan beberapa temannya yang beragama Katolik membantu mengelola sekolah kecil gratis untuk anak-anak miskin di Pakistan. Suatu pagi di tahun 2013, sebuah peringatan yang ditandatangani oleh kelompok Muslim militan diselipkan di bawah pintu kantor sekolah.
“Berhenti memberikan pendidikan dakwah kepada anak-anak Muslim. Jika tidak, kami akan menembak Anda dan anak-anak Anda,” demikian isi ancaman tersebut, yang dilihat oleh The Associated Press.
Sepuluh hari kemudian, sekolah menerima peringatan lain – kali ini dengan peluru. Relawan sekolah mengajukan pengaduan ke polisi; AP melihat salinan dokumen tersebut, yang dicap oleh polisi setempat untuk menunjukkan bahwa mereka telah menerimanya. Pernyataan pasangan tersebut dikonfirmasi oleh beberapa orang yang dihubungi AP.
Pasangan tersebut mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak Muslim, namun mengajarkan kisah-kisah Alkitab dan doa kepada anak-anak Kristen ketika teman sekelas mereka yang Muslim tidak ada. Mereka mengatakan bahwa anak-anak Muslim terkadang berkeliaran, mendengar doa dan mengaji di rumah.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan kelompok agama minoritas di Pakistan semakin teraniaya – tidak hanya umat Kristen, namun juga umat Hindu dan Ahmadiyah, sebuah sekte Islam yang ditolak oleh kelompok Muslim arus utama. Mereka mengatakan bahwa meskipun tidak ada seorang pun yang dieksekusi berdasarkan undang-undang penistaan agama yang ketat di negara tersebut, undang-undang tersebut digunakan untuk mengancam non-Muslim dan menghasut kekerasan massa. Pada bulan November, sepasang suami istri beragama Kristen dibunuh oleh massa karena diduga menodai Al-Quran.
Diperkirakan 12.000 agama minoritas telah meninggalkan Pakistan sejak tahun 2009, menurut Farrukh Saif, yang memimpin kelompok advokasi minoritas yang mendukung pencari suaka di Bangkok.
Pasangan yang diancam tersebut melarikan diri ke Thailand karena teman-temannya mengatakan bahwa mendapatkan visa turis mudah dan karena orang Kristen lainnya telah pergi ke sana.
“Orang-orang mengatakan kepada kami: ‘Selamatkan hidupmu terlebih dahulu, lalu khawatirkan hal-hal lain’,” kata sang ayah.
Setelah bersembunyi selama sebulan, mereka mengemas dua koper barang-barang mereka dan menaiki penerbangan tengah malam ke Bangkok.
___
Ketika mereka tiba di ibu kota Thailand yang beruap, rasa lega dengan cepat berubah menjadi kecemasan.
Makanannya, bahasanya — semuanya baru. Sang ayah pergi ke UNHCR untuk mendaftar sebagai pencari suaka dan terkejut saat mengetahui bahwa ia harus menunggu dua tahun – hingga September 2015 – hanya untuk mendapatkan wawancara pertamanya dalam proses “penentuan status pengungsi”. Kini, bagi pendatang baru, penantiannya adalah tiga tahun.
Badan PBB tersebut memiliki lebih dari 60 staf di Bangkok yang bekerja untuk memverifikasi cerita ribuan pencari suaka dan menentukan apakah mereka adalah pengungsi yang mempunyai ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, kata Girard dari UNHCR. Setiap kasus harus diselidiki untuk menyingkirkan mereka yang mencoba mengeksploitasi sistem, seperti mereka yang diperdagangkan melalui jaringan penyelundupan.
“Kita harus sangat ketat dalam mengenali siapa yang benar-benar pengungsi dan siapa yang bukan,” katanya.
Bagi mereka yang menunggu, uang dengan cepat menjadi masalah.
Setelah menghabiskan tabungan mereka, keluarga Pakistan tersebut mengunjungi gereja untuk mendapatkan dukungan. Kebanyakan menolaknya. Akhirnya, sebuah sidang menawarkan sekitar $100 sebulan.
Sang ibu mendapat pekerjaan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak Thailand. Dia mendapat penghasilan 8.000 baht ($250) sebulan, cukup untuk membayar sewa, utilitas, dan makanan.
Sang ayah, yang telah menganggur selama berbulan-bulan, baru-baru ini mendapatkan pekerjaan di sebuah taman kanak-kanak, namun hal ini berarti ketiga anaknya sendirian di flat sepanjang hari. Dan kini kedua orang tuanya bisa ditangkap karena bekerja ilegal.
“Saat saya berangkat kerja, saya tidak tahu apakah saya akan kembali menemui anak-anak saya atau tidak,” kata sang ayah.
Mereka yang ditangkap biasanya berakhir di Rumah Detensi Imigrasi. Satu-satunya jalan keluar adalah membayar biaya penerbangan pulang Anda sendiri atau akhirnya menetap di luar negeri. Beberapa masih ditahan selama bertahun-tahun.
Veerawit Tianchainan, direktur eksekutif Komite Pengungsi Thailand, mengatakan pemerintah Thailand khawatir bahwa mengakui pencari suaka dan pengungsi akan menarik lebih banyak pengungsi. Dia mengatakan lokasi Thailand dan kemudahan akses akan menarik orang-orang yang putus asa, dan reformasi diperlukan untuk mengatasi kenyataan tersebut.
Kementerian-kementerian pemerintah telah mengadakan pembicaraan informal mengenai undang-undang yang akan melindungi pencari suaka dan pengungsi selama satu tahun, tanpa memberikan hak untuk bekerja, kata Veerawit.
Sihasak Phuangketkeow, sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan usulan tersebut patut mendapat perhatian serius namun belum dipertimbangkan secara formal.
___
Wawancara pertama dengan PBB bisa jadi menimbulkan trauma.
Masyarakat diminta untuk memberikan bukti penganiayaan. Beberapa dari mereka menangis atau tidak bisa mengekspresikan diri mereka dengan jelas, kata Medhapan Sundaradeja, direktur Asylum Access di Thailand, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan nasihat gratis kepada para pencari suaka.
Keputusan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kasusnya ditolak, meskipun pencari suaka dapat mengajukan banding.
File orang-orang yang diakui sebagai pengungsi kemudian dikirim ke negara-negara tuan rumah potensial untuk dipertimbangkan untuk pemukiman kembali, sebuah proses yang biasanya memakan waktu 12 hingga 18 bulan.
Namun dari sekitar 860.000 pengungsi paling rentan di seluruh dunia yang diyakini membutuhkan pemukiman kembali pada tahun 2013, hanya 80.000 tempat yang tersedia. Amerika menyumbang sekitar 70 persen dari jumlah tersebut.
Ayah asal Pakistan itu mengatakan mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Dia yakin apa yang akan dilakukan para ekstremis Muslim jika dia kembali: “Saya tahu mereka akan membunuh kami berdua, istri saya dan saya, dan mereka tidak akan membiarkan anak-anak saya.”
Jadi dia menunggu dan memimpikan kehidupan di mana mereka tidak perlu bersembunyi dan anak-anaknya bisa bersekolah dengan bebas.
“Kami hanya ingin pergi ke tempat yang aman bagi hidup kami,” katanya sambil menghela nafas, “dan kami mempunyai kebebasan.”
__
Reporter Associated Press Adil Shakeel di Karachi, Pakistan berkontribusi pada laporan ini.
___
Ikuti Malcolm Foster di Twitter di http://twitter.com/mjfosterap