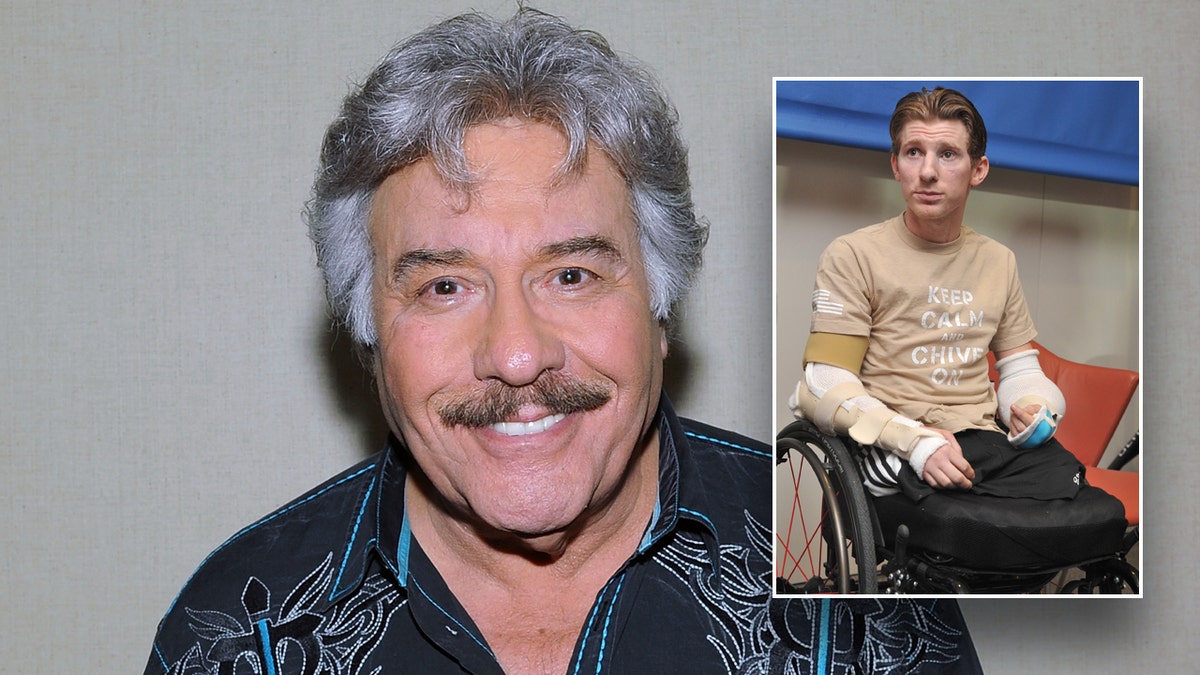Tiada tempat yang senyaman rumah: Warga Afrika menyelesaikan perjalanan epik ke Eropa, bertanya-tanya apakah tujuannya sepadan dengan semua usaha yang dilakukan
Dalam foto bertanggal 13 Juni 2015 ini, Jean Paul Apetey berlatih bahasa Jerman di tempat penampungan pencari suaka di Otter, Jerman utara. Apetey menikmati kedatangan yang terorganisir dengan baik dan hangat di negara bagian Lower Saxony, Jerman utara. (Foto AP/Dalton Bennett) (Pers Terkait)
CREIL, Perancis – Melawan rintangan, Hamed Kouyate mencapai impian masa kecilnya untuk keluar dari kemiskinan di Afrika dan mencapai jantung Eropa yang kaya. Namun seperti banyak migran lainnya yang mengalami pengembaraan rahasia yang ditandai dengan kerja keras dan teror, remaja tersebut kini mempertanyakan apakah ia hanya mempertaruhkan nyawanya pada ilusi yang kejam.
“Eropa tidak punya emas atau berlian untuk saya. Saya harus tidur nyenyak dan tidak makan selama berhari-hari sejak saya tiba di Prancis. Tidak ada yang seperti yang saya bayangkan,” kata remaja berusia 18 tahun itu sambil berjalan. tepi sungai di pinggiran kota Paris, Creil, tiga tahun perjalanan dan lebih dari 5.000 mil (8.000 kilometer) dari rumahnya di Pantai Gading. “Saya menyesal meninggalkan Afrika. Saya tidak akan merekomendasikan rute ini bahkan kepada musuh terburuk saya.”
Sejak bulan Januari, The Associated Press telah mengikuti kelompok beranggotakan 45 orang warga Afrika Barat saat mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan penyelundupan yang sempit dari Yunani ke Hongaria melalui Balkan. Rute tersebut, yang dapat diakses dari Turki yang dipenuhi pengungsi yang melarikan diri dari barbarisme ISIS, sudah menjadi cara terpopuler kedua untuk mendapatkan akses ilegal ke 28 negara Uni Eropa dan dua tujuan terbesarnya: Jerman dan Perancis. Gelombang migran dari Asia, Arab, dan Afrika yang belum pernah terjadi sebelumnya memilih rute yang lambat dan melelahkan, bukannya menyeberang laut dari Afrika Utara, rute yang lebih cepat namun nekat menuju Italia. Ribuan orang yang melakukan perjalanan itu telah tenggelam di Mediterania selama setahun terakhir.
Kouyate dan beberapa migran lainnya yang diwawancarai oleh AP mendokumentasikan risiko-risiko yang dihadapi di Balkan: kereta api malam yang mematikan yang menghancurkan traktor-traktor yang terjebak di punggung bukit, jembatan dan di dalam terowongan; perampokan yang dilakukan oleh kelompok kriminal dan polisi korup yang berkeliaran seperti burung nasar di sepanjang jalan; penyelundup menyandera kliennya, memperkosa perempuan dan memukuli laki-laki, sampai kerabat jauh mentransfer uang ekstra; menimbulkan rasa lapar dan haus yang mengejutkan, karena pendakian diperkirakan akan berlangsung selama berhari-hari hingga berminggu-minggu.
Trauma itu seharusnya tidak sia-sia, para pelancong terus berkata pada diri mereka sendiri di setiap kemunduran yang brutal. Pada bulan April, mereka akhirnya mencapai Hongaria, dari sana mereka dapat melakukan perjalanan ke Jerman dan Prancis dengan taksi jitney dan jaringan transportasi umum di wilayah UE yang sebagian besar bebas paspor. Sebagian besar warga Afrika Barat mencapai tujuan mereka pada bulan Mei, setelah membayar sejumlah penyelundup Asia dan Afrika lebih dari 5.000 euro ($5.500) ke setiap jalur dalam rantai penyelundupan dari Turki hingga perbatasan timur UE untuk mendapatkan perlindungan.
Meskipun Jerman terbukti relatif murah hati terhadap pendatang, Perancis menghadapi ujian yang lebih berat. Jerman tidak mengizinkan para pencari suaka untuk bekerja sementara kasus mereka diselidiki, namun Jerman sering kali menyediakan perumahan berkualitas tinggi bagi para pendatang baru di daerah pinggiran kota disertai dengan pembayaran bulanan yang hanya tiga digit. Sebaliknya, Kouyate mengatakan dia menerima pembayaran tunggal sebesar 40 euro ($45) di Prancis, yang mana dia berpindah dari sofa ke tempat tidur, ke bangku parkir, dan kembali lagi.
Jerman menerima 202.834 pencari suaka pada tahun 2014 – hampir sepertiga dari total pencari suaka di Uni Eropa – dan diperkirakan akan melipatgandakan jumlah tersebut untuk mencapai rekor tertinggi pada tahun ini. Kanselir Angela Merkel secara terbuka berjanji untuk melipatgandakan pengeluaran pemerintah federal untuk pencari suaka dan bulan ini menjanjikan tambahan 1 miliar euro kepada otoritas negara bagian dan lokal untuk memastikan semua pendatang baru memiliki tempat tinggal dan dapat mengikuti pendidikan bahasa Jerman, yang merupakan hal wajib untuk mendapatkan tempat tinggal.
Hal ini merupakan gambaran yang sangat berbeda di Perancis, yang telah menerima lebih dari 250.000 orang asing sebagai pengungsi – banyak dari mereka adalah penutur bahasa Perancis yang berasal dari bekas wilayah kolonial seperti Pantai Gading – dan menerima 101.895 pencari suaka lainnya pada tahun lalu, yang merupakan jumlah pencari suaka terbesar kedua di Uni Eropa. , menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Kantor Perlindungan Pengungsi dan Ekspatriat Perancis hanya mampu menampung sepertiga pelamar baru secara langsung, sementara banyak yang tidur di luar, di stasiun kereta api atau bar tenda.
Penantian untuk mendapatkan izin tinggal di negara bagian biasanya dapat berlangsung selama satu tahun – saat para migran telah kalah dalam kasus pengadilan mereka dan telah kehabisan hak untuk tetap tinggal di negara tersebut.
Pengadilan imigrasi Perancis kini menerima kurang dari seperlima pelamar. Mereka lebih memilih kandidat dari zona perang aktif seperti Suriah, bukan migran ekonomi dari Pantai Gading yang miskin namun relatif damai, tempat kudeta berdarah dan perang saudara selama satu dekade telah berkurang sejak tahun 2011.
Prospek penolakan masih belum terasa bagi Kouyate. Dia menyerahkan diri ke polisi dua kali sebelum mendapatkan rujukan ke otoritas perlindungan anak, yang membantunya mendapatkan tempat di asrama pemuda yang didanai negara. Dia sekarang berharap untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pesepakbola profesional, sebuah ambisi yang tampaknya tidak masuk akal mengingat dia gagal mencapai tujuan tersebut di Turki yang kurang kompetitif. Dia telah ditolak oleh beberapa klub Prancis yang mengatakan mereka tidak dapat mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan bermain tanpa dokumentasi tempat tinggal yang tepat.
Tanpa gentar, Kouyate tampaknya tidak puas dengan segala hal tentang Prancis kecuali sepak bola.
“Sepak bola adalah hasrat saya. Karena sepak bola saya berada di Eropa. Pada bulan September saya akan berlatih bersama tim,” katanya, seraya menyebutkan bahwa ia saat ini kekurangan sepatu sepak bola.
“Asrama akan membelikan saya sepatu bola dan mereka akan mendaftarkan saya ke sebuah tim,” desaknya.
Sekitar 500 mil (800 kilometer) ke arah timur laut, rekan perjalanannya dari Pantai Gading Jean Paul Apetey dan Hilarion Charlemagne menikmati kedatangan yang terorganisir dengan baik dan hangat di negara bagian Lower Saxony, Jerman utara. Berbeda dengan Kouyate, mereka jauh lebih bahagia dengan lingkungan yang disediakan negara di kota-kota pertanian di selatan Hamburg, dimana stroberi dan asparagus putih mendominasi lanskapnya. Keduanya fokus belajar bahasa Jerman dengan cukup cepat untuk menunjukkan keseriusan mereka dan mengesankan tuan rumah, untuk mendapatkan akomodasi dan mulai mendapatkan uang yang dapat mereka wariskan kepada anak-anak mereka.
Charlemagne telah mengenakan sepasang sepatu rusak yang ia kenakan sejak Yunani, termasuk saat berjalan-jalan di Makedonia selama lebih dari dua minggu yang diinterupsi polisi. “Saya tidak akan membutuhkan sepatu ini lebih lama lagi,” kata guru berusia 45 tahun itu.
Pihak berwenang Jerman menempatkan dia dan tiga migran Afrika Barat lainnya di sebuah rumah dua apartemen yang baru direnovasi di kota Brietlingen, berpenduduk 3.400 jiwa. Para tetangganya, seorang pasangan lanjut usia asal Jerman, tidak bisa berbahasa Prancis dan tidak tahu di mana letak Pantai Gading. Charlemagne menyebut wanita berusia 70-an itu dengan sebutan “Oma”, yang berarti nenek dalam bahasa Jerman.
Wanita tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa keluarganya meninggalkan negara asal mereka, Polandia, pada tahun 1945 ketika Rusia mendekat, jadi dia menceritakan “rasa ketidaktahuan” orang Afrika sebagai pendatang baru.
Charlemagne dan Apetey, mantan tentara Pantai Gading berusia 34 tahun, masing-masing menerima sekitar 140 euro ($157) sebulan untuk menutupi pengeluaran, dan tunjangan tersebut bisa meningkat menjadi lebih dari 300 euro ($335) setiap bulan pada bulan depan.
Apetey ditempatkan di bekas hotel yang telah direnovasi di pusat Otter, sebuah kota berpenduduk hampir 1.500 jiwa, beberapa di antaranya belum pernah melihat wajah Afrika secara langsung. Fasilitas bergaya asrama perguruan tinggi ini dibuka tiga bulan lalu dan telah menampung lebih dari 40 migran dari seluruh Afrika dan Timur Tengah.
Dia berbagi kamar dengan seorang warga Pantai Gading dan dua orang Bosnia lainnya, yang dia akui tidak percaya, terutama karena mereka tidak dapat berbicara satu sama lain. Dia mencurigai tetangga Libya mencuri uang kertas 20 euro dari kamarnya, tapi dia tidak bisa menghadapinya secara langsung karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Yang paling menyebalkan, katanya, adalah pemain keyboard Arab amatir yang ada di sana. “Dia mengerikan,” kata Apetey sambil tertawa.
Hubungan dengan warga setempat lebih baik. Untuk menunjukkan solidaritas, sekitar 20 penduduk desa mengadakan pesta penyambutan di rumah baru para pengungsi, membawakan kue mangkuk dan permainan papan serta mengubah ruang tamu asrama yang luas menjadi “kafe internasional” untuk bermalam.
“Anda benar-benar tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui, tapi saya bisa membayangkannya dan saya merasa kasihan karenanya,” kata Maduria Roeper, seorang konsultan gaya hidup berusia 59 tahun, Apetey tersenyum tidak mengerti di sampingnya. “Mereka pasti melewati masa-masa sulit… semacam trauma.”
Roeper mengatakan beberapa penduduk desa menentang penampungan orang asing di Otter, namun sebagian besar bertekad “untuk membuat jembatan bagi para pencari suaka, untuk mengurangi rasa takut, hambatan… dan benar-benar bagi mereka dari hati kami untuk menunjukkan bahwa kami ingin berintegrasi mereka.”
Apetey mengatakan dia menghargai keramahtamahan Jerman, terutama pendekatan polisi yang informatif dan bersahabat, yang kontras dengan setiap kekuatan Uni Eropa lainnya yang pernah dia alami mulai dari Yunani hingga Austria. Namun ia khawatir bahwa masa istirahatnya sebagai tunawisma akan berumur pendek, dan pihak berwenang Jerman akan menolak permohonannya untuk mendapatkan status pengungsi. Hal ini telah terjadi pada teman-teman Pantai Gading yang telah mengajukan banding terhadap perintah deportasi. Dia mencatat bahwa kartu izin tinggal sementara miliknya hanya memiliki masa berlaku tiga bulan.
“Saya mengenal orang-orang yang melakukan perjalanan yang sama dengan saya, yang mendapatkan kartu tersebut dan tiga bulan kemudian mereka menerima surat yang mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan Jerman,” katanya. “Kami pencari suaka. Kami tidak punya apa-apa! Saya tidak punya kontak. Saya banding ke siapa? Dengan uang apa? Anda dapat pengacara, itu uang.”
Di Prancis, Kouyate menyatakan bahwa sebagian dari dirinya tidak keberatan untuk kembali ke rumah. Dia mengatakan masyarakat Afrika menikmati lingkungan yang lebih bahagia dan solidaritas sosial yang lebih besar, dan membandingkan hal ini dengan seringnya dia melihat orang-orang Eropa tanpa perasaan berjalan melewati pengemis jalanan.
Tapi Kouyate mengatakan dia harus tetap bertekad dan sukses di Eropa karena orang tuanya telah mengorbankan ribuan uang tunai kepada penyelundup dan agen sepak bola. Ia tidak ingin investasi mereka sia-sia.
“Ini sebenarnya bukan rasa bersalah. Ini soal harga diri,” katanya. “Ketika orang tua menghabiskan begitu banyak uang untuk menyekolahkan anaknya ke Eropa, jarang sekali anak tersebut menghindar dari tantangan… jadi saya tidak bisa kembali begitu saja.”
___
Laporan Pogatchnik dari Dublin. Reporter Associated Press Raphael Satter di Istanbul dan Kirsten Grieshaber di Berlin berkontribusi pada laporan ini.