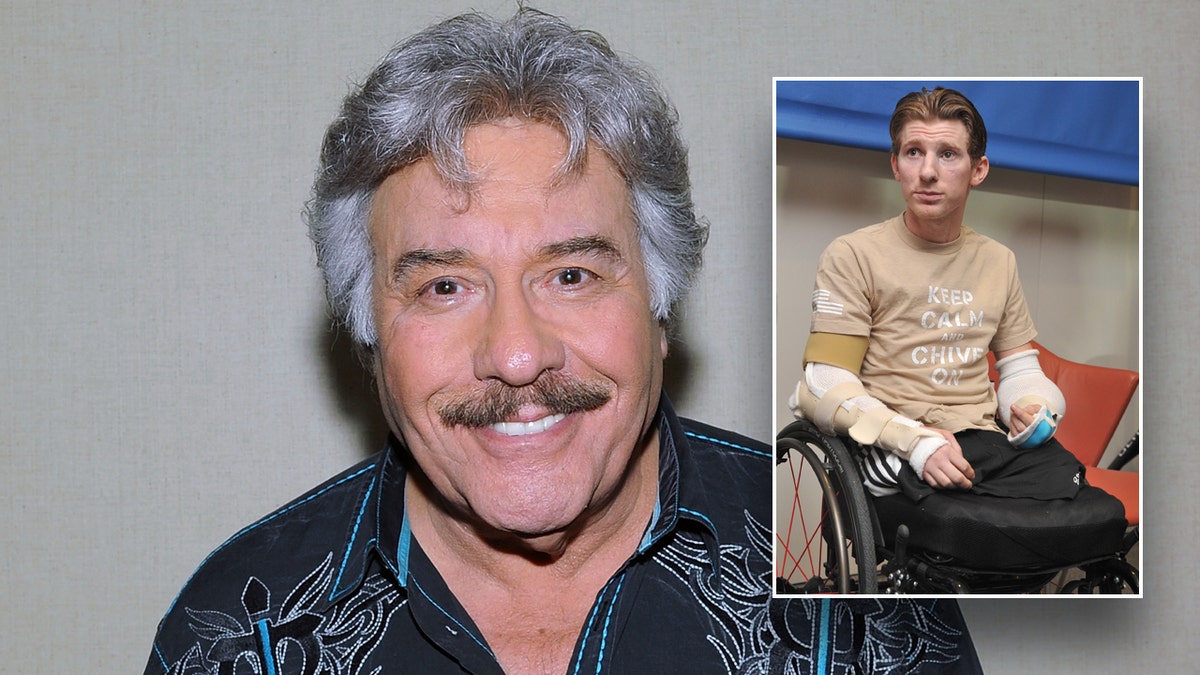Kaum ‘tak tersentuh’ di Yaman terjebak dalam baku tembak perang
SANAA, Yaman – Mereka adalah orang-orang Yaman yang tak tersentuh.
Mereka menyebut diri mereka “Muhammasheen,” atau “kaum marginal,” sebuah kelompok etnis berkulit gelap yang selama berabad-abad terlantar di peringkat sosial terbawah di Yaman, dihadapkan pada diskriminasi dan rasisme, serta dijauhi oleh orang lain. Mereka tinggal di daerah kumuh di pinggiran kota, sering kali tidak bersekolah dan melakukan pekerjaan kasar seperti semir sepatu atau membersihkan jalan, atau terpaksa mengemis. Warga Yaman lainnya secara tradisional menyebut mereka “Akhdam” atau “pelayan”.
Di negara yang menganggap kepemilikan suatu suku sangat penting untuk menjamin perlindungan, status, dan penghidupan, komunitas mereka – yang menurut beberapa perkiraan berjumlah hampir 3 juta orang – tidak memiliki suku dan diabaikan oleh pemerintah.
Akibatnya, mereka sangat terpukul dalam perang saudara di Yaman, yang mempertemukan pemerintah, yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi, melawan pemberontak Syiah yang dikenal sebagai Houthi dan pasukan yang setia kepada presiden terguling Yaman.
Lingkungan mereka telah terkena serangan udara koalisi dan penembakan Houthi, menghancurkan rumah-rumah sementara mereka yang terbuat dari lembaran logam, karton dan selimut.
Banyak dari mereka yang terpaksa harus mengungsi tanpa ada seorang pun yang mau menampung mereka. Ada pula yang bercerita tentang pelarian diri dari serangan yang dilakukan oleh satu pihak, namun kemudian dihantam lagi oleh faksi lain dan kombatan yang terlibat dalam konflik tersebut. Kelompok-kelompok Yaman yang mendistribusikan bantuan kemanusiaan mengabaikan mereka, kata mereka.
“Kami telanjang. Kami tidak punya apa-apa,” kata Houssna Mohammed ketika dia berdiri di dekat sisa-sisa gubuknya yang hangus di daerah kumuh kaum marginal di kota Taiz di bagian barat. Dia mengatakan rumahnya terbakar pada bulan Maret ketika mortir menghantam tetangganya dan api melalap gubuknya.
Walid Abdullah, seorang anggota kelompok Marginalisasi berusia 20 tahun, mengatakan bahwa kampung halamannya di Taiz, al-Jahmaliya, dilanda penembakan pada awal perang. Seluruh komunitas yang terdiri dari 200 keluarga mengungsi ke al-Rahda, kota lain di provinsi Taiz. Kemudian mereka harus melarikan diri lagi ketika serangan udara Saudi menghantam al-Rahda.
Sekarang dia berada di Sanaa, ibu kota Yaman, dan dia mengatakan keluarganya tersebar di berbagai daerah kumuh di kota tersebut. Dalam serangan udara tersebut, ia kehilangan satu-satunya sumber pendapatannya, sebuah sepeda motor yang ia tawarkan untuk disewakan. “Sekarang aku tidak punya apa-apa,” katanya.
Diperkirakan 9.000 orang tewas dalam pertempuran di Yaman pada tahun lalu, dan lebih dari 2,4 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Jumlah korban tewas di kalangan kaum marginal sulit diverifikasi karena hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Salah satu kelompok advokasi, Organisasi Yaman Melawan Diskriminasi, mengatakan mereka telah mendokumentasikan lebih dari 300 orang terbunuh, termasuk 68 anak-anak dan 56 perempuan. Yahia Said, ketua organisasi tersebut, mengatakan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.
Asal muasal Muhammasheen tidak jelas. Tradisi populer mengatakan bahwa mereka adalah keturunan tentara Ethiopia yang menginvasi Yaman pada abad ke-6. Teori lain menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Afrika yang termasuk orang pertama yang mendiami kota-kota pesisir di Yaman.
Statistik resmi pemerintah menyebutkan populasi mereka sekitar 500.000, namun aktivis yang terpinggirkan mengatakan jumlah mereka sekitar 3 juta. UNICEF memperkirakan jumlah mereka sekitar 10 persen dari populasi, atau 2,6 juta jiwa.
Selama beberapa generasi mereka diperlakukan sebagai kelas bawah permanen. Warga Yaman menyebut mereka najis dan melarang anak-anak mereka bergaul dengan mereka. Salah satu pepatah umum di kalangan masyarakat Yaman adalah, “Bersihkan piringmu jika disentuh oleh seekor anjing, dan pecahkanlah jika disentuh oleh seorang Khadem.”
Para aktivis mengatakan sekolah dan rumah sakit sering kali menolak mereka. Mereka mengatakan perempuan di komunitas tersebut rentan terhadap pelecehan seksual oleh warga Yaman lainnya, yang yakin bahwa pengadilan tidak akan mengadili mereka atau bahwa suku mereka akan mengintimidasi kelompok marginal agar diam. Sebaliknya, jika laki-laki yang terpinggirkan diyakini berteman dengan perempuan asing, seluruh komunitasnya dapat diusir dari rumah mereka sebagai hukuman.
Anak-anak kelompok marginal yang menentang stigma sosial dan bersekolah sering kali dilecehkan oleh guru dan sesama siswa. Said mengenang bagaimana, ketika ia duduk di bangku kelas satu, gurunya menuduh orang kulit hitam di Yaman sebagai keturunan orang-orang yang mencoba menghancurkan Ka’bah, situs paling suci umat Islam, yang terletak di Mekkah. Hal ini mengacu pada peristiwa sejarah di mana seorang raja Yaman yang beragama Kristen Ethiopia mengirim pasukan dengan gajah untuk menghancurkan Ka’bah.
“Bayangkan 70 siswa memandang saya dengan jijik,” kenang Said.
Saleh al-Bair mempelajari ilmu politik di universitas-universitas di Uni Soviet dan Kuba pada tahun 1990-an, salah satu dari sedikit kelompok marginal yang mendapatkan akses terhadap pendidikan di luar negeri. Namun, dia kini bekerja sebagai penyemir sepatu di Sanaa.
Dia mengatakan bahwa bahkan sebelum perang, komunitasnya tidak memiliki hak.
“Jika Anda pergi ke pengadilan, hakim tidak akan menuntut saya dengan menyebut nama, tapi akan berkata, ‘pelayan’. Jadi keadilan seperti apa yang Anda harapkan setelah itu?” katanya.
Pada tahun 2014, UNICEF melakukan survei terhadap lebih dari 9.000 keluarga marginal di kota Taiz, salah satu komunitas terbesar mereka. Laporan tersebut menemukan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan, semuanya jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional. Hanya separuh anak-anak yang bersekolah, 80 persen orang dewasa dan hampir 52 persen anak usia 10-14 tahun buta huruf. Lebih dari separuh anak di bawah usia 1 tahun tidak diimunisasi.
Buthaina al-Iryani, spesialis perlindungan sosial di UNICEF, mengatakan badan tersebut mendistribusikan uang tunai kepada keluarga kaum marginal di Sanaa dan Taiz karena kebutuhan mendesak mereka. Namun dia mengakui: “Itu hanya setetes air di lautan.”
Kini, setelah satu tahun perang, mereka benar-benar tersingkir dari hierarki sosial.
Lebih dari sebelumnya, mengemis telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka. Anak-anak bertelanjang kaki dengan rambut kusut, wajah tertutup debu, terlihat tidur di jalan sementara ibu mereka yang berjubah hitam menjangkau pejalan kaki dan meminta uang.
“Situasi kemanusiaan sangat menyedihkan,” kata Noaman al-Houzifi, ketua Persatuan Nasional Kaum Marginalisasi. Sementara yang lain memiliki suku atau kerabat kaya yang membantu atau melindungi mereka jika mereka harus meninggalkan rumah, “bagi mereka yang terpinggirkan, mereka tidak punya apa-apa.”
Ia dan aktivis marginal lainnya mengatakan operator lokal yang mendistribusikan bantuan kemanusiaan telah mengecewakan mereka.
“Bahkan selimut yang didistribusikan oleh kelompok bantuan dan bantuan, kaum marginal tidak diperbolehkan menerima bantuan tersebut,” kata Misk al-Maqmari, seorang aktivis marginal berusia 25 tahun yang menjalankan kelompok lokal bernama Enough.
Di rumah sakit, korban luka akibat perang yang terpinggirkan seringkali tidak diberi tempat tidur atau perawatan dan dibiarkan mati, katanya. “Seolah-olah mereka adalah binatang. Bahkan binatang pun mempunyai hak.”
___
Michael melaporkan dari Kairo.