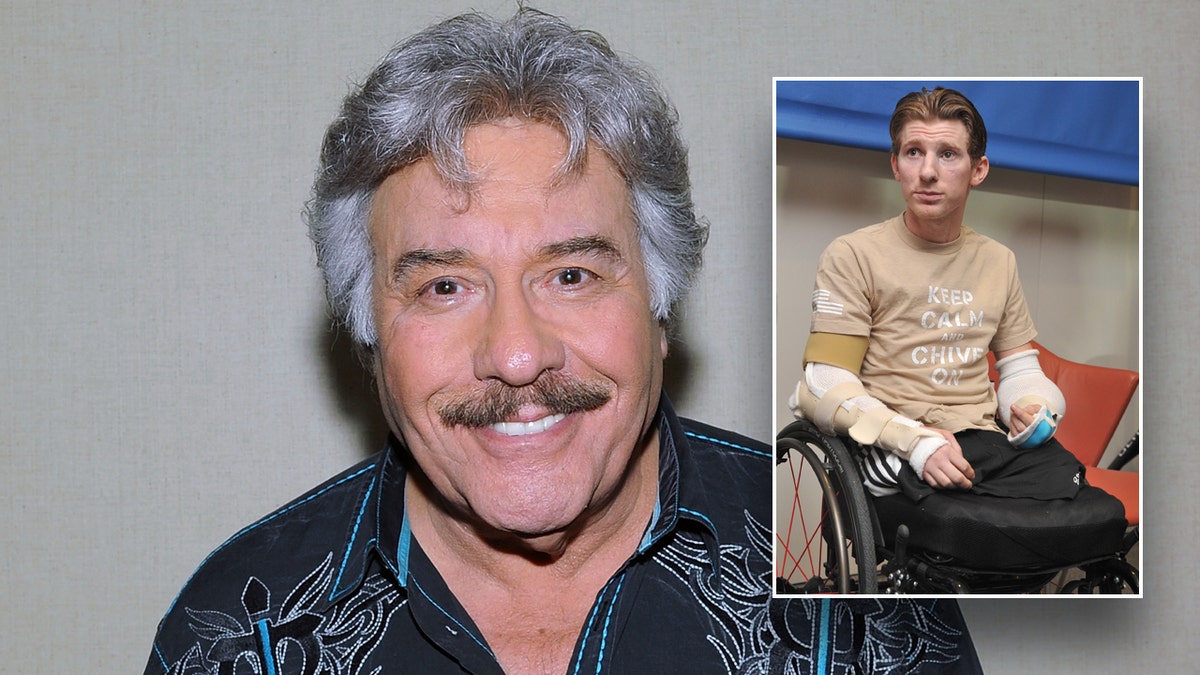Media Asia mengkritik kekerasan senjata di AS, rasisme setelah penembakan di Charleston

BEIJING – Seringkali menjadi sasaran dakwaan hak asasi manusia di AS, Tiongkok tidak membuang waktu untuk membalas dakwaan tersebut setelah penembakan di sebuah gereja bersejarah bagi warga kulit hitam di Carolina Selatan yang menewaskan sembilan orang. Di wilayah lain di Asia, serangan tersebut memperbarui persepsi bahwa warga Amerika mempunyai terlalu banyak senjata dan masih perlu mengatasi ketegangan rasial.
Beberapa orang mengatakan serangan itu memperkuat kekhawatiran mereka tentang keselamatan pribadi di AS – terutama sebagai orang asing non-kulit putih – sementara yang lain mengatakan mereka masih merasa aman untuk berkunjung.
Khususnya di Australia dan Asia Timur Laut, di mana senjata api dikontrol dengan ketat dan kekerasan bersenjata hampir tidak pernah terjadi, banyak orang yang terkejut dengan tekad banyak orang Amerika untuk memiliki senjata meskipun terjadi penembakan massal berulang kali, seperti tragedi tahun 2012 di Sekolah Dasar Sandy Hook di Newtown. , Connecticut, di mana seorang pria bersenjata membunuh 20 anak-anak dan enam orang dewasa.
“Kami tidak memahami kebutuhan Amerika akan senjata,” kata Philip Alpers, direktur proyek GunPolicy.org di Universitas Sydney, yang membandingkan undang-undang senjata di seluruh dunia. “Ini sangat membingungkan bagi orang non-Amerika.”
Sebagai negara perbatasan seperti AS, Australia memiliki sikap serupa terhadap senjata api sebelum penembakan massal tahun 1996 yang menewaskan 35 orang. Segera setelah itu, pembatasan ketat terhadap kepemilikan senjata diberlakukan dan tidak ada insiden serupa yang dilaporkan sejak saat itu.
Ahmad Syafi’i Maarif, seorang intelektual terkemuka Indonesia dan mantan pemimpin Muhammadiyah, salah satu dari dua organisasi Muslim terbesar di negara ini, mengatakan tragedi tersebut telah mengejutkan banyak orang di mana pun.
“Orang-orang di seluruh dunia percaya bahwa rasisme hilang dari AS ketika Barack Obama terpilih dua kali untuk memimpin negara adidaya,” katanya. “Tetapi penembakan di Charleston mengingatkan kita bahwa benih-benih rasisme masih tetap ada dan tertanam di hati komunitas kecil di sana, dan bisa meledak kapan saja, seperti aksi terorisme yang dilakukan oleh individu.”
Seorang pria kulit putih berusia 21 tahun, Dylann Storm Roof, dituduh menembak dan membunuh sembilan orang di sebuah studi Alkitab di Gereja Episkopal Metodis Afrika Emanuel Afrika yang bersejarah di Charleston, Carolina Selatan. Seorang kenalannya mengatakan bahwa Roof mengeluh bahwa “orang kulit hitam mengambil alih dunia”.
Penembakan bermuatan rasial di AS telah mendapat perhatian global yang luas. Agustus lalu, protes pecah di Ferguson, Missouri, setelah seorang petugas polisi kulit putih menembak dan membunuh seorang pria kulit hitam berusia 18 tahun yang tidak bersenjata.
Komentator sosial terkemuka Malaysia Marina Mahathir mengatakan banyak orang di negaranya merasa bingung mengapa pemerintah AS tidak membatasi undang-undang kepemilikan senjata. Amandemen Kedua Konstitusi AS melindungi hak untuk memiliki dan memanggul senjata.
“Kami bingung dengan kebebasan senjata di sana. Ini adalah gagasan yang aneh bahwa setiap orang harus mempunyai hak untuk memiliki senjata,” kata Marina, putri mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.
Penulis dan pembuat film dokumenter India Sohail Hashm mengatakan budaya senjata di Amerika terkait dengan diskriminasi rasial dan desakan Amerika untuk menjadi polisi dunia.
“Semua orang (di Amerika) suka punya senjata. Itu budaya dominan karena itulah yang mereka bangun,” kata Hashmi. “Dan dengan senjata yang tersedia secara bebas, apakah mengherankan jika insiden seperti ini terjadi?”
Di Tiongkok, kantor berita resmi Xinhua mengatakan kekerasan di Carolina Selatan “mencerminkan kurangnya tindakan pemerintah AS terhadap kekerasan bersenjata yang merajalela serta meningkatnya kebencian rasial di negara tersebut.”
“Kecuali pemerintahan Presiden AS Barack Obama benar-benar merenungkan masalah-masalah yang mengakar di negaranya seperti diskriminasi rasial dan kesenjangan sosial serta mengambil tindakan nyata mengenai pengendalian senjata, tragedi seperti itu tidak akan bisa dicegah agar tidak terjadi lagi,” kata Xinhua dalam sebuah editorial.
Di layanan mikroblog Weibo yang mirip Twitter di Tiongkok, beberapa pengguna membandingkan Amerika Serikat dengan Somalia yang tidak punya hukum, dan mengatakan bahwa diskriminasi rasial memicu kekerasan dan tingginya tingkat kejahatan. Banyak pihak yang mengutarakan pandangan resmi bahwa kepemilikan senjata dan kejahatan dengan kekerasan adalah produk sampingan dari kebebasan demokratis gaya Barat yang tidak hanya tidak sesuai bagi Tiongkok tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana.
Mengingat pembunuhan baru-baru ini terhadap mahasiswa Tiongkok dan mahasiswa asing lainnya di Amerika, pekerja kantoran Xie Yan mengatakan dia masih ingin mengunjungi Amerika tetapi akan “sangat berhati-hati” di sana.
Xie mengatakan dia telah mendengar banyak tentang rasisme di AS namun tidak yakin dengan dinamika yang mendasarinya.
“Kita cenderung melihat AS sebagai tempat yang penuh kekerasan, tapi menurut saya kita tidak terlalu memahami rasisme di sana. Orang Tionghoa bebas belajar di sana, berkunjung, dan tinggal di sana, jadi rasanya tidak ada diskriminasi di sana. ” Kata Xu sambil menunggu kereta di Subway 1 yang sibuk di Beijing.
Seperti Australia, Tiongkok juga mempunyai masalah dengan diskriminasi ras dan etnis. Tiongkok didominasi oleh satu kelompok etnis, Han, dan para aktivis mengecam kurangnya kesadaran mengenai diskriminasi pekerjaan dan perumahan yang dihadapi oleh kelompok minoritas seperti warga Tibet dan Muslim Uighur Turki dari wilayah barat laut.
Polisi Tiongkok telah dituduh melakukan taktik kekerasan terhadap mereka yang dicap sebagai separatis atau teroris, meskipun tindakan tersebut tampaknya didukung oleh sebagian besar warga Tiongkok.
Di Jepang, diskriminasi cenderung tidak didasarkan pada warna kulit dibandingkan asal negara, sehingga menimbulkan prasangka terhadap orang Tiongkok dan Korea, kata Hiroko Takimoto, 41, seorang pengacara paten di Tokyo.
Pembunuhan rasial adalah “sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat Jepang,” katanya.
Yukari Kato, wakil presiden perusahaan Ryugaku Journal yang membantu pelajar Jepang dalam program luar negeri, termasuk sekitar 2.000 pelajar di AS, mengatakan kekerasan bukanlah hal baru dan sebagian besar negara masih aman.
“Tidak ada bedanya dengan Jepang. Ada tempat di mana Anda bisa menjadi korban kejahatan. Anda hanya harus bersiap untuk membela diri,” ujarnya.
Namun, Yuka Christine Koshino, 21, seorang mahasiswa ilmu politik di Universitas Keio Tokyo, mengatakan dia sangat terpukul dengan penembakan tersebut, terutama setelah berpartisipasi dalam kampanye kesadaran rasisme saat belajar di Universitas California, Berkeley. Interaksi tersebut memberinya harapan bahwa situasinya membaik. Penembakan itu “mengejutkan” saya, kata Koshino.
Ketua Aliansi Pengacara Hak Asasi Manusia Filipina, Max de Mesa, berbagi sentimen dengan aktivis hak-hak sipil di Carolina Selatan yang menunjukkan bahwa bendera pertempuran Konfederasi, simbol Selatan yang pro-perbudakan selama Perang Saudara, terus berkibar. negara, bahkan saat mereka berduka atas sembilan orang yang terbunuh.
“Beberapa struktur (lama) dan beberapa sikap tetap ada dan bahkan dijunjung tinggi, setidaknya sekarang terlihat,” kata de Mesa.
“Tidak ada bedanya dengan pelaku bom bunuh diri,” katanya. “Bagi seorang jihadis: ‘Saya akan bersama Allah jika saya melakukan ini.’ Yang lain mengatakan: ‘Saya membuktikan supremasi kulit putih di sini.’
Intelektual Indonesia Syafi’i Maarif berharap insiden tersebut dapat membantu Amerika berhenti menyamakan terorisme dengan Islam.
“Terorisme dan radikalisme dapat muncul di setiap lapisan masyarakat dengan berbagai samaran dan mengatasnamakan suku, agama, dan ras,” ujarnya.