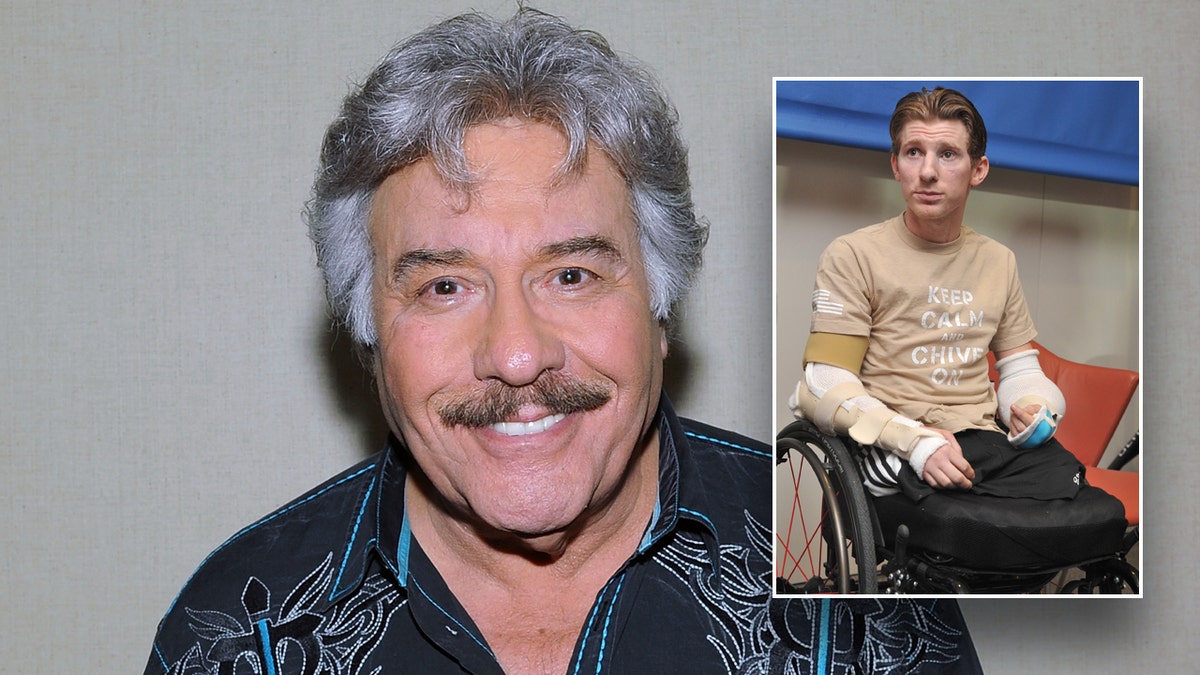Perjalanan seorang anak untuk memahami perang dan kehidupan ayahnya
Setiap Natal ketika saya masih kecil di awal tahun 1960-an, ibu saya akan memberi saya dorongan melalui lubang di loteng kami. Saya akan membuang kotak-kotak kosong yang disimpan di sana untuk membungkus kado. Di dekatnya ada sebuah koper berisi memorabilia Perang Dunia II yang dibawa ayah saya dari pertempuran di Pulau Pasifik.
Ada manual kode Marinir AS. Kartu pendaratan rahasia. gambar Jepang. Dan barang-barang lainnya, termasuk paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Kekaisaran Jepang.
Ketika saya sudah cukup umur untuk menyelinap ke sana, saya menatap foto mug di paspor seorang pria yang lembut. Namanya Seiichi Zayasu – ditulis dalam bahasa Jepang dan Inggris. Ayah saya, Steve Maharidge, harus membunuhnya untuk mendapatkan dokumen tersebut. Siapa Tuan? Zayasu? Sedikit yang saya tahu bahwa saya akan mengetahuinya beberapa dekade kemudian.
(tanda kutip)
Ayah tidak pernah berbicara banyak tentang perang. Dia terkadang memiliki temperamen yang meledak-ledak. Saya menghubungkannya dengan keberadaannya dalam perkelahian. Sebagai seorang anak laki-laki, saya bermimpi untuk pergi bersamanya ke lokasi perang sehingga saya dapat memahami sifat buruknya.
Dia meninggal pada tahun 2000 dengan peran perang dalam hidupnya masih menjadi misteri.
Saya kemudian menghabiskan 12 tahun berikutnya untuk mencari 29 orang dari unitnya. Saya mengetahui bahwa dia menderita dua gegar otak di Okinawa dan ledakan mortir yang hampir fatal di Guam pada tahun 1944.
Ayah sembuh dari luka berdarahnya. Namun para ahli mengatakan kepada saya bahwa dia pasti menderita cedera otak traumatis, TBI. Otak tidak sembuh. Ini menjelaskan emosinya, yang merupakan gejala TBI.
Saya sudah bisa menerima kemarahannya. Namun masih ada urusan yang belum selesai. Saya harus mengembalikan paspor ke keluarga Zayasu.
Saya terbang ke Okinawa dan pergi ke desa Okuma dengan seorang penerjemah. Alamat Seiichi adalah lahan kosong. Di seberang jalan ada sebuah rumah dengan nama: “Zayasu.”
Dipenuhi rasa takut, saya mengetuk. Seorang lelaki tua membuka pintu. Seijin Zayasu memberitahuku bahwa dia adalah sepupu Seiichi.
“Sepertinya ayahku membunuh pamanmu,” aku mendengkur.
Saat kata-kataku diterjemahkan, kebingungan memenuhi wajah Seijin, yang berubah menjadi ekspresi yang mengira aku gila. Seiichi terlalu tua untuk direkrut – dia berusia 49 tahun pada tahun 1945, kata Seijin. Dia meninggal dalam kecelakaan konstruksi tahun 1952. Seiichi, istri dan tujuh anaknya melarikan diri ke pegunungan sebelum pendaratan Amerika pada tanggal 1 April 1945.
Saya telah membentuk narasi palsu sepanjang hidup saya. Ayah masuk ke rumah mereka yang kosong. Dia adalah seorang pencuri, bukan pembunuh dalam kasus ini. Aku membayangkan Ayah tertawa di suatu tempat. Itu adalah hal yang menurutnya lucu. Aku senang ayahku tidak membunuh Seiichi.
Saya menemukan jalan ke Moritake Zayasu, putra Seiichi. Pada tahun 1945 dia berumur sepuluh tahun. Propagandis militer Jepang mengatakan bahwa Amerika akan menembak warga sipil, sehingga keluarga tersebut bersembunyi sampai pertempuran selesai.
Orang tua Moritake tidak kecewa karena mereka melewatkan sesuatu ketika sampai di rumah. Mereka senang masih hidup. Mereka adalah salah satu dari sedikit keluarga Okinawa yang tidak kehilangan siapa pun selama pertempuran 82 hari tersebut. Diperkirakan 150.000 warga sipil tewas, sebagian besar akibat penembakan dan pemboman AS.
Moritake bertanya mengapa ayahku menyimpan paspornya. Dia tidak marah, hanya bingung. Saya tidak punya jawaban. Semua orang, kecuali satu orang yang saya temui di perusahaan Ayah, mengambil oleh-oleh dari mayat dan rumah. Mungkin Ayah melihatnya sebagai sesuatu yang “eksotis”, sebuah tanda mengingat perjalanannya ke belahan dunia lain untuk melawan orang-orang yang tidak dibencinya.
Ed Hoffman, yang berada di perusahaan Ayah, memiliki foto Jepang. Pada tahun 1990-an, dia mengirim mereka ke surat kabar Okinawa dengan harapan keluarga mereka dapat melihatnya. Banyak cerita saat ini tentang orang Amerika yang mengambil kembali barang-barang dari perang hampir 70 tahun yang lalu.
Apa yang memotivasi kita melakukan hal ini?
Mungkin kitalah yang mencoba mengatasi kegilaan perang. Negara-negara terlibat dalam konflik, namun dampak akhirnya tidak ditanggung oleh politisi atau jenderal.
Ayah saya tidak ingin ikut serta dalam Perang Dunia II – dia mengabaikan tiga rancangan pemberitahuan pada tahun 1943 dan hanya “menjadi sukarelawan” untuk Marinir setelah polisi datang. Sebagai warga sipil, keluarga Zayasu juga tidak menginginkan perang.
Ayah saya tidak berdaya melawan benturan antar bangsa. Meskipun khayalan saya untuk datang ke Okinawa bersamanya tidak pernah terwujud, saya merasa bahwa dia ada bersama saya dalam roh ketika saya mencari kesembuhan dalam satu tindakan kecil yang dapat saya kendalikan untuknya.
“Ayahku masuk ke rumahmu,” kataku pada Moritake, “dan mengambil beberapa barang. Jadi, aku minta maaf atas namanya, dan mengembalikannya padamu.”
Saya merinci barang-barang selain paspor yang dilampirkan – termasuk dompet dan foto bayi.
Sampai saat itu, Moritake masih dicadangkan. Matanya melebar sekarang.
“Saya pikir itu mungkin saya!” Seru Moritake sambil memegang gambar bayi itu.